Kamp Cideng
Kamp Cideng | |
|---|---|
 Bagian luar beberapa rumah di kamp interniran Cideng (1945). Setiap rumah menampung hingga dua puluh wanita dan anak-anak. | |
| Negara | Kerajaan Belanda |
| Koloni | Hindia Belanda |
| Kota | Batavia |
| Dibuka | 1942 |
| Ditutup | 1945 |
| Pendiri | Kekaisaran Jepang |
Kamp Cideng adalah kamp interniran yang dikelola Jepang untuk wanita dan anak-anak selama Perang Dunia II, di bekas Hindia Belanda (sekarang Indonesia).
Kekaisaran Jepang memulai invasi ke Hindia Belanda pada 10 Januari 1942. Selama pendudukan Jepang, yang berlangsung hingga berakhirnya perang pada September 1945, orang-orang keturunan Eropa dikirim ke kamp-kamp interniran. Sebagian besar orang yang ditawan adalah orang Belanda, tetapi juga orang Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia. Kamp-kamp Jepang digambarkan oleh para mantan tahanan sebagai kamp konsentrasi atau kamp pemusnahan pasif; karena penahanan makanan dan obat-obatan dalam skala besar dan terus-menerus, sejumlah besar tahanan meninggal seiring berjalannya waktu.[1][2][3]
Kamp Cideng

Kamp Cideng terletak di kota Batavia (sekarang Jakarta), ibu kota Hindia Belanda. Sebagian dari Cideng, daerah pinggiran di sebelah barat kota, dipagari dan digunakan untuk menampung wanita dan anak-anak Eropa. Para pria dan anak laki-laki yang lebih tua dipindahkan ke kamp-kamp lain, termasuk kamp tawanan perang. Tempat tinggal bervariasi dari bungalow bata dengan atap genteng hingga gubuk yang dibuat dengan gaya tradisional Jawa dari bambu.[4]
Awalnya Cideng disebut sebagai 'daerah lindung' oleh Jepang dan di bawah otoritas sipil. Kondisinya dapat ditoleransi. Ketika militer Jepang mengambil alih kendali pada bulan April 1944, hak-hak istimewa seperti diizinkannya memasak atau mengadakan kebaktian gereja segera dicabut. Penyiapan makanan terpusat dan kualitas serta kuantitas makanan menurun drastis. Kondisi kehidupan memburuk. Sistem pembuangan air limbah rusak. Kelaparan dan penyakit melanda, dan karena obat-obatan dan perawatan medis tidak diberikan, jumlah kematian meningkat. Kematian akibat infeksi dan kekurangan gizi menjadi kejadian sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, Jepang mengurangi ukuran kamp berkali-kali, sementara kamp tersebut terpaksa menampung lebih banyak tahanan. Awalnya, ada sekitar 2.000 wanita dan anak-anak. Pada akhir perang, populasi kamp tersebut sekitar 10.500 orang. Luas tanah telah dikurangi menjadi seperempat dari ukuran aslinya. Setiap bagian ruang digunakan untuk tidur, termasuk dapur yang tidak terpakai dan kamar mandi yang tidak memiliki air.
Dari April 1944 hingga Juni 1945, kamp tersebut berada di bawah komando Kapten Kenichi Sone. Sone bertanggung jawab atas banyak kekejaman. Ia bertanggung jawab atas pengurangan jatah makanan, pencukuran kepala, dan pemukulan. Ia menyelenggarakan 'kumpulan' atau absensi di mana wanita, anak-anak, dan orang sakit harus berdiri di bawah terik matahari tropis selama berjam-jam. Setelah perang, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 2 September 1946. Hukuman itu dilaksanakan oleh regu tembak Belanda pada 7 Desember, setelah permintaan pengampunan kepada letnan gubernur jenderal Belanda, Hubertus van Mook, ditolak. Istri Van Mook adalah salah satu tahanan Sone.[5][6]
Setelah serangan nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945. Pada tanggal 16 September, Palang Merah Internasional membuat rekaman film tentang para wanita di Cideng. Gambar-gambar tersebut ditayangkan di bioskop-bioskop Belanda pada film berita Polygoon pada minggu pertama bulan Desember. Ini adalah gambar-gambar film pascaperang pertama yang ditayangkan di Belanda dari Hindia Belanda.[7][8]
Ketika Letnan Kolonel Read-Collins dari Sekutu tiba di kamp setelah Jepang menyerah, ia menyaksikan sendiri keadaan para tawanan. Pengamatannya telah dicatat dalam The Knights of Bushido: A History of Japanese War Crimes During World War II, oleh Lord Edward Russell, penasihat hukum pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo.[9]
"Tidak ada fasilitas apa pun, tidak ada tempat bermain bagi anak-anak, dan mereka hanya bisa berolahraga di jalan-jalan sempit yang, selama musim hujan, tergenang air limbah setinggi mata kaki dari tangki septik yang meluap. Penyakit yang paling umum adalah penyakit kekurangan gizi seperti edema [kelaparan] dan beri-beri. Disentri dan malaria juga merajalela."
Dia mencatat tidak adanya kekurangan makanan di Batavia, berbeda dengan situasi di kamp:
"Makanan pokoknya adalah nasi dalam jumlah yang tidak mencukupi, terkadang sedikit daging, roti hitam asam yang terbuat dari tepung tapioka, dan sedikit daun obi, satu-satunya sayuran. Segera setelah Jepang menyerah, jatah makanan para tawanan digandakan. Tidak ada kekurangan makanan di Batavia sebelum kembalinya Sekutu dan [Letnan Kolonel] Read-Collins tidak melihat tanda-tanda kekurangan gizi di antara penduduk asli setempat. Pada tanggal 18 September, sudah ada seribu dua ratus pasien di rumah sakit kamp. Ada banyak orang lain yang seharusnya dirawat di rumah sakit tetapi tetap dirawat demi anak-anak mereka. Ketika mereka semua dirawat, jumlah pasien meningkat menjadi dua ribu, dan setiap bangunan yang tersedia di Batavia diubah menjadi rumah pemulihan. Banyak kasus terburuk dievakuasi ke Singapura."
Reuni keluarga
Setelah pembebasan, para lelaki yang selamat dari kamp kerja paksa Jepang datang mencari istri dan anak-anak mereka. Sepasang suami istri menggambarkan reuni tersebut:[10]
"Setelah perang, saya dipindahkan ke rumah sakit Carolus di Batavia bersama anak-anak. Saya berada di sebuah ruangan bersama enam orang wanita. Suami saya datang dari Bandung mencari saya. Ia melihat ke sekeliling ruangan dan ke arah saya. Kemudian ia berkata kepada biarawati itu: 'Suster, istri saya tidak ada di sini'. Jadi saya memanggilnya, 'Paul!' Saya melihatnya memejamkan mata. Seperti: 'oh, tidak, itu tidak mungkin benar'. Saya pasti terlihat mengerikan. Dada saya seperti papan cuci. Berat badan saya 35 kg dan sebagian besar rambut saya rontok."
"Saya juga tidak mengenali anak-anak itu. Yang termuda mengalami pembengkakan karena kelaparan dan memiliki kerak cokelat di kepalanya. Yang lainnya memiliki kaki kurus. Anak-anak itu tidak tumbuh sama sekali selama tiga tahun."
Akibat

Setelah Jepang menyerah, periode Bersiap yang penuh kekerasan pun dimulai. Kata 'bersiap' dalam bahasa Indonesia berarti 'bersiap' atau 'bersiaplah'. Dalam kekosongan kekuasaan, Soekarno membuat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menandai dimulainya Revolusi Nasional Indonesia. Ribuan orang Eropa dan Eurasia dibunuh oleh penduduk asli Indonesia. Perkiraan jumlah kematian warga sipil Belanda sebagai akibat dari Bersiap berkisar antara 3.500 hingga 30.000 orang. Bekas kamp interniran Jepang menjadi tempat berlindung yang aman.[11][12][13]
Pada bulan Desember 1945, 3.800 korban selamat dari kamp, termasuk 1.200 anak-anak, dipulangkan ke Belanda dengan kapal SS New Amsterdam. Anak-anak tersebut lemah setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kamp interniran Jepang. Campak merebak di atas kapal, dan banyak anak meninggal. Korban yang meninggal dikubur di laut. Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana dari Belanda menandatangani perjanjian yang menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.[14]
Pemulangan ke Belanda

Banyak imigran dari Hindia Belanda yang belum pernah ke Belanda. Mereka sering kehilangan harta benda selama pendudukan Jepang atau harus meninggalkan harta benda mereka. Belanda berjuang melawan kekurangan perumahan dan pengangguran. Beberapa orang yang datang dari Hindia Belanda ditempatkan sementara di bekas kamp kerja paksa Perang Dunia II, seperti kamp transit Westerbork. Pemerintah Belanda awalnya mencoba mencegah imigrasi dari Hindia Belanda, tetapi karena situasi di koloni itu memburuk, para imigran diizinkan masuk ke negara itu dengan persyaratan yang ketat. Pengalaman traumatis di kamp-kamp Jepang atau periode Bersiap sering tidak dibahas.[15][16][17]
Dalam literatur
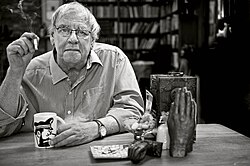
Penulis Belanda Jeroen Brouwers menggambarkan pengalaman masa kecilnya di kamp, dan dampaknya di kemudian hari, dalam novel otobiografi tahun 1986 Bezonken Rood, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Sunken Red. Terjemahan bahasa Prancisnya memenangkan penghargaan sastra Prix Femina pada tahun 1995.
Clara Olink Kelly dalam bukunya tahun 2003 The Flamboya Tree, dan Boudewijn van Oort dalam bukunya tahun 2008 Tjideng Reunion, menulis tentang kehidupan dan kondisi di kamp, dan van Oort juga menjelaskan secara rinci latar belakang militer dan diplomatik. Henri Charles Schmid menceritakan kehidupan ibunya selama dipenjara di kamp Cideng dalam bukunya tahun 2014 Scattered Journey. Robine Andrau dalam bukunya tahun 2015 Bowing to the Emperor: We Were Captives in WWII, yang ditulis bersama ibunya, menggambarkan pengalaman mereka di kamp dan pengalaman ayahnya sebagai tawanan perang di Jepang.[18][19]
"Ibu saya juga dipukuli, dicukur, dan dipaksa berdiri di lapangan absen selama dua puluh empat jam. Saya melihatnya di sana. Entah apa yang dilakukan padanya yang tidak saya lihat. Di rumah kami di kamp, saya pergi ke ruang depan tempat Nettie Stenvert tinggal. Ibu Nettie Stenvert berbaring telentang di atas meja, tanpa sehelai pakaian pun, kedua kakinya terangkat dan terbuka. Di antara kedua kakinya berdiri seorang Jepang yang telah menurunkan celananya, sehingga saya tertawa terbahak-bahak karena ini benar-benar hal terlucu yang pernah saya lihat, meskipun selama bertahun-tahun di kamp, saya akan melihatnya beberapa kali lagi dengan berbagai cara, tetapi saya tidak akan tertawa." (Dari: Jeroen Brouwers, Sunken Red)
Selebritas Belanda yang ditahan di Cideng
- Christel Adelaar
- Jeroen Brouwers
- Tonke Dragt
- Boudewijn de Groot (ibunya meninggal di Cideng saat dia berusia satu tahun)[20]
- Teun Koolhaas
- Aarnout Loudon
- Petronella Rutte-Dilling, istri pertama Izaäk Rutte. Izaäk adalah ayah dari mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. Petronella meninggal di Cideng pada tanggal 20 Juli 1945.[21]
Referensi
- ^ Prisoners of the Japanese: Civilian internees, Pacific and South-East Asia. Australian War Memorial.
- ^ Japanse concentratiekampen. Oorlogsverhalen.nl (in Dutch).
- ^ Vrouwen aan het woord in documentaire over Japanse kampen. NOS, 29 maart 2024 (In Dutch).
- ^ Tjideng Prison Camp. Tjideng Reunion.
- ^ Tjideng Camp. Peter van der Kuil.
- ^ Sonei Trial. Sentence by Ch.W.A. Abbenhuis, 2 September 1946.
- ^ Een voorbeeldige kolonie. Nederlands-Indië in 50 jaar overheidsfilms 1912-1962. G.A. Jansen Hendriks, 2014 (In Dutch).
- ^ Tjideng Prison Camp Batavia (film). Imperial War Museum.
- ^ Edward Frederick Langley Russell. The Knights of Bushido: A History of Japanese War Crimes During World War II. Cassell, 1958.
- ^ Bloemen voor de doden. De Japanse kampen in Nederlandsch-Indië. Hein van Dooren, Weekuit, Eindhovens Dagblad (In Dutch).
- ^ Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (cijfers). NIOD.nl (in Dutch).
- ^ De bevrijding en Bersiap in Kamp Tjideng. Geschiedenisvanzuidholland.nl (In Dutch).
- ^ Frederick, W. H. (2012). The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s national revolution (1945–49): a ‘brief genocide’ reconsidered. Journal of Genocide Research, 14(3–4), 359–380.
- ^ Doden repatriëringsschip herdacht. NOS, zondag 11 augustus 2013 (In Dutch).
- ^ Nooit meer terug naar Indië: 'Zo Nederlands worden als de Nederlanders'. NOS Nieuws, 15 augustus 2020 (In Dutch).
- ^ 'Wat komen jullie hier doen?' Documentaire door Pia Media in opdracht van Omroep MAX, 1 juni 2017 (In Dutch with English subtitles).
- ^ 'We zaten met het hele gezin op een klein koud kamertje'. AVROTROS, EenVandaag, 15 augustus 2020 (In Dutch).
- ^ Literatuur. Tjidengkamp.nl (In Dutch).
- ^ Schmid, Henri (October 2014). Scattered Journey. ISBN 978-0692304402.
- ^ Mijn moeder overleed in Tjideng, ik ken haar alleen van foto’s. Boudewijndegroot.nl (In Dutch).
- ^ Persoonlijke Rutte over zijn vader in het jappenkamp: ‘Toen hij eruit kwam, bezat hij enkel wat hij aan had’. Laurens Kok, AD, 15 augustus 2020.
External links
- Peter van der Kuil: Tjideng Camp.
- 3 min. 48 sec. video of Tjideng internment camp after liberation.

